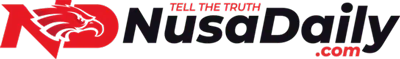Peran Agama dalam Mewujudkan Transformasi Sosial
Oleh: Pdt. Dr. Sugiyanti Supit, S.Th., M.Pd.K.

Agama telah lama memainkan peran yang signifikan sebagai penggerak utama dalam menginspirasi dan mendorong perubahan sosial dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang beragam, agama telah menjadi sumber inspirasi, moralitas, dan identitas kolektif. Hal itu mempengaruhi cara manusia berinteraksi, berorganisasi, bahkan membangun struktur sosial yang penuh harmoni, damai dan sejahtera.
Menurut Nurhadi Sucahyo (2023), dalam rangka pelaksanaan pemilu di Indonesia, maka isu polarisasi agama dikaitkan dengan politik menjadi atensi dari berbagai pihak. Pemimpin Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah menekankan dalam penjelasannya tentang isu polarisasi agama bahwa isu ini tidak boleh diabaikan karena berdampak konflik yang mempengaruhi perubahan sosial masyarakat Indonesia.
Indonesia rupanya berhadapan dengan fenomena polarisasi agama terkait politik. Agama seringkali dijadikan wadah untuk mendapatkan dukungan politik, dan sebaliknya sehingga dapat bermuara pada ketegangan sosial bahkan konflik yang dapat dikaitkan dengan keberadaan agama.
Atensi terhadap isu di atas menjadi pertanyaan tentang bagaimana agama dapat mempengaruhi perubahan sosial, dalam konteks yang semakin dinamis dan beragam. Kompleksitas dan relevansi tentang peran agama sebagai agen perubahan dalam menghadapi tantangan dan peluang zaman ini menjadi hal menarik yang perlu dibahas.
Transformasi Sosial dan Tantangan Kontemporer
Manusia memiliki peran yang sangat penting terkait konteks perubahan sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki beberapa ungkapan seperti zoon politicon hewan yang bermasyarakat (Socrates), animal rational (hewan yang berpikir), animal simbolocum (binatang yang memahami lambang-lambang), homofaber (manusia yang menciptakan alat- alat), homo educandun (manusia yang terdidik), homo politicus (manusia yang berpolitik), homo economicus (manusia ekonomik), das kranke tier = hewan yarg sakit (Max Scheller), hewan yang bermoral, dan lain-lain.
Seorang pakar antropologi dan spikologi yang pernah mendapat penghargaan pulitzer tahun 1974, Becker menegaskan bahwa manusia adalah pencipta sosial sekaligus makhluk asosial. Melalui penggunaan kekuatan linguistik secara sosial, manusia menciptakan identitasnya sendiri. Hanya dengan kinerja yang tepat dalam konteks sosial, maka manusia walaupun secara individu dapat membentuk dan memperbarui dirinya melalui tindakan yang bertujuan dalam dunia yang memiliki makna secara bersama. Artinya manusia tidak dapat disetarakan dengan makhluk lainnya seperti pendapat Darwin.
Perubahan menciptakan tantangan bagi manusia. Kingley Davis menjelaskan bahwa kebutuhan alam dan ekonomi selalu menjadi tantangan bagi manusia. Melalui interaksinya dengan lingkungan alam, dan melalui interaksinya dengan sesamanya, manusia dapat menciptakan situasi yang kondusif di mana ia meningkatkan kemampuan intelektual yang melekat pada keberadaannya.
Oleh karena itu, manusia harus dapat mengatasi kebutuhan dan permasalahan utama masyarakat (populasi), pembagian fungsi (spesialisasi), kohesi timbal balik antara individu dengan masyarakat (solidaritas), dan pelestarian masyarakat melalui banyak generasi.
Manusia dalam realitasnya, bersosialisasi dalam dunia masyarakat yang kompleks dengan warna hidup yang berbeda-beda. Eksistensi masyarakat menurut Collins adalah kekuatan yang besar, sehingga bisa menghidupkan tetapi juga menghancurkan manusia. Manusia bergantung kepada masyarakat karena kekuatan yang luar biasa itu.
Masyarakat adalah entitas dinamis yang mengalami perubahan dalam berbagai aspek seperti struktur, nilai, norma dan perilaku. Dalam hal ini yang dimaksud dengan perubahan sosial seperti yang dikatakan Davis adalah struktur dan fungsi masyarakat. Perubahan sosial dapat dikatakan sebagai studi tentang fenomena perubahan fisik (ledakan penduduk, migrasi, bencana alam), inovasi teknologi, perubahan demografi, ekonomi, dan pengaruh budaya.
Dengan demikian, sosiologi perubahan akan membantu agama untuk mengetahui sejauh mana tercapainya fungsi agama dalam masyarakat post modern. Dinamika yang menjadi realitas terhadap perubahan di atas mengundang suatu upaya dan strategi sebagai senjata bagi manusia dan masyarakat dalam menciptakan suatu kehidupan yang lebih inklusif, berkelanjutan dan berdaya. Penggunaan teori-teori sosiologi perubahan dalam memahami keberadaan keagamaan, sangatlah penting karena berdampak pada bagaimana memperkaya agama dan melanggengkan fungsinya dalam perubahan budaya masyarakat.
Agama Sebagai Motor Perubahan Sosial.
Untuk lebih jelasnya maka perlu dipahami konsep tentang agama terkait perubahan sosial. Hargrove berpendapat bahwa agama adalah fenomena kemanusisan yang berfungsi menyatukan sistem budaya, sosial, dan personal menjadi satu kesatuan yang bermakna.
Beberapa komponen menurut Barbara Hargrove dapat dibagi dalam beberapa hal yaitu: (a) Komunitas pemeluk agama yang memiliki kesamaan; (b) Kesamaan mitos yang menafsirkan abstraksi nilai-nilai budaya ke dalam sejarah realitas melalui; (c) Perilaku ritual yang memungkinkan partisipasi pribadi; (d) Dimensi pengalaman yang diakui mencakup sesuatu yang lebih dari realitas sehari-hari-yang suci.
Durkheim (1966) seorang sosiolog Perancis mengemukakan secara panjang lebar tentang agama. Menurutnya, agama memiliki peran yang krusial dalam mempertahankan kohesi sosial sambil mengatur perilaku setiap manusia dalam masyarakat. Agama tidak terbatas pada suatu kepercayaan atau praktek keagamaan semata tetapi juga soal moralitas sosial. Nilai-nilai, norma, dan simbol-simbol dibentuk oleh agama dalam rangka membatasi kehidupan mansuia dalam suatu komunitas sosial.
Dalam pandangannya Durkheim sebenarnya memberikan penegasan bahwa representasi agama di dunia tidak hanya memelihara stabilitas sosial melainkan menjadi motor perubahan signifikan dalam masyarakat.
Dengan demikian agama tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. manusia tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat. Agama, manusia, dan masyarakat adalah tiga hal yang selalu berjalan beriringan dan tak bisa dipisahkan. Mereka ada dalam suatu eksistensi sosial.
Sebagai motor perubahan sosial maka agama dapat memobilisasi manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mengadvokasi suatu perubahan yang ada dalam bidang politik, juga mengedepankan masalah kemanusiaan yang mengglobal. Namun peran agama sebagai motor perubahan sosial dihadapkan dengan beberapa tantangan terkait fungsi agama yang sejati. Selain itu, tantangan yang tidak dapat diabaikan yaitu: konflik internal antar agama, ketidakseimbangan kekuasaan, dan interpretasi agama yang berbeda-beda antara yang satu dengan lainnya.
Artinya, untuk mencapai peran agama yang sejati maka dibutuhkan pemahaman komprehensif yang didukung oleh analisis secara mendalam terhadap dinamika sosial, politik dan budaya masyarakat.
Transformasi Sosial dan Keagamaan di Indonesia
Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagamaan yang tinggi karena ada berbagai agama yang berkembang secara harmonis. Ada enam agama yang diakui di Indonesia yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Transformasi sosial di Indonesia tercermin dalam dinamika keagamaan yang kompleks. Dapat dilihat dari interaksi antara berbagai agama terjadi baik secara positif dan konflik serta mengalami perubahan seiring waktu. Persatuan nasional Indonesia kembali diuji periode 1945-1965 dengan berbagai peristiwa krusial yang muncul dalam kerusuhan rasial, tuntutan otonomi etnik, dan konflik agama.
Transformasi sosial terkait dengan dinamika politik dan identitas Indonesia. Agama seringkali dipergunakan sebagai alat dalam rangka mencapai tujuan politik sehingga mempengaruhi cara orang memandang dan memperlakukan keagamaan. Sejarah membuktikan ada banyak pengalaman yang terjadi terkait agama dan politik. Belajar dari pengalaman tidak menyenangkan yang berujung pada kudeta komunis pada tanggal 30 September 1965, bangsa ini mendeklarasikan pembuktian persatuan Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila.
Ketika Indonesia memasuki era baru yang disebut Orde Baru, maka saat itu disebut sebagai titik balik politik Indonesia untuk memasuki negara modern mulai tahun 1967. Pembangunan ekonomi dan modernisasi negara menjadi tujuan utama yang ingin dicapai. Sejak akhir tahun 1970-an, pemerintah dengan persetujuan DPR menyatakan bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas kehidupan sosial dan politik Indonesia. Hal ini memperkuat persatuan Indonesia. Hal inilah yang menarik banyak sarjana untuk melakukan penelitian tentang Pancasila sebagai Dasar Agama Sipil Indonesia (Susan Purdy, 1983).
Agama-agama yang ada di Indonesia terus menerus menginterprestasikan dirinya sambil mencoba untuk mempertahankan program pembangunan ekonomi. Namun di sisi lain dalam agama terdapat kelompok yang mengritik ketimpangan keadilan dalam bidang ekonomi dan politik. Hal ini terlihat dari protes keagamaan yang diungkapkan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.
Agama mengartikulasikan nilai-nilai dan keharusan sistem sosial dan melalui proses sosialisasi tidak hanya memberikan identitas individu tetapi juga melekatkannya pada tujuan-tujuan sosial. Di tingkat masyarakat, agama berperan sebagai kekuatan yang menstabilkan masyarakat dan berfungsi untuk melegitimasi, melalui berbagai tingkat kontrol sosial, menetapkan nilai-nilai, tujuan, dan pola kepemimpinan.
Di sisi lain, agama dapat dimanipulasi dalam masyarakat, melalui kontrol sosial atau pemaksaan, misalnya sebagai instrumen dominasi politik. Dengan demikian transformasi sosial dan keagamaan memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Transformasi sosial keagamaan di Indonesia merupakan refleksi dari dinamika kompleks dalam masyarakat yang terus berubah. (***)
Pdt. Dr. Sugiyanti Supit, S.Th., M.Pd.K. adalah Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen (FIPK) Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado, dan anggota Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humaniora Indonesia (PISHI).
Editor: Wadji